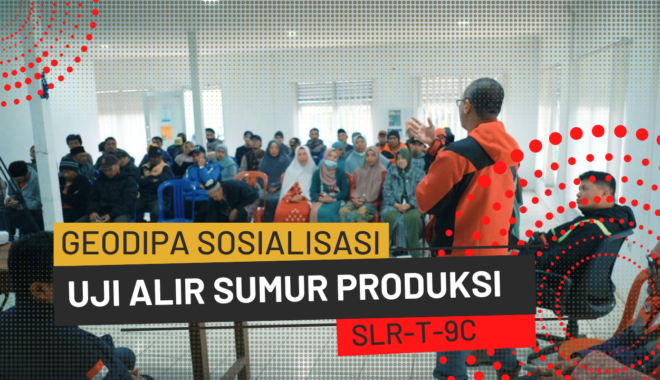Oleh: M. Faizi, Petani Sekaligus Jurnalis Media Serikat-News
Tulisan kedua ini, saya sedang tidak ingin bicara soal cinta. Namun, bagaimana kalau diksi cinta itu saya jadikan sebuah metafora.
Ceritanya begini, beberapa hari terakhir ini di tengah kesibukan saya sebagai seorang petani, saya juga ikut menikmati kehebohan tentang kisah Anjali dan Rahul di TikTok. Ceritanya sederhana, klise, bahkan Anjali menyimpan perasaan kepada Rahul, tetapi perasaan itu tidak pernah sampai. Belum sempat diucapkan, datanglah Tina Malhotra yang merebut perhatian Rahul, membuat Anjali memilih menjauh, menghilang dalam kecewa.
Dalam tren ini, netizen kerap menulis kalimat pembuka: “Rahul, apa kabar?”
Kalimat itu seolah mewakili luka lama yang tidak pernah diselesaikan. Bukan karena tidak ingin, akan tetapi karena tidak diberi kesempatan.
Bermula dari hal tersebut, saya tiba-tiba berpikir: Anjali saya posisikan sebagai masyarakat dan Rahul adalah negara, sedangkan Tina, ya, itu para pemilik pabrik rokok yang tak pernah benar-benar hidup, tetapi terus mendapat jatah pita cukai.
Dari kisah tersebut, saya mulai catatan sederhana berbalut metafora ini dari obrolan warung kopi saja karena bagi saya tidak ada yang lebih jujur daripada obrolan di warung kopi. Di sana, kebenaran sering telanjang tanpa takut ditutup-tutupi oleh sopan santun birokrasi atau seragam pegawai negeri.
Di suatu sore, saya mendengar satu celetukan yang bunyinya agak ekstrem, “Sumenep disebut sebagai surganya rokok ilegal.” Awalnya saya anggap itu cuma lelucon warung. Namun, setelah saya telusuri pelan-pelan, rupanya dugaan itu nyaris mendekati kebenaran.
Lebih dari sekadar rokok ilegal, kini Sumenep punya model baru industri bayangan: ternak pita cukai. Fenomena ini bahkan lebih licin, lebih rapi dan lebih menyebalkan dari sekadar produksi tanpa izin.
Modelnya sederhana, tetapi rumit untuk dibongkar. Pabrik rokok didirikan, secara administratif resmi bahkan dengan seremoni dan potong pita. Plang besar bertuliskan nama perusahaan dipasang mencolok, lengkap dengan cat mengilap dan pagar tinggi.
Begitu masuk ke dalam, yang Anda temukan adalah kesunyian. Tak ada dengung mesin, tak ada hiruk-pikuk buruh bahkan bau tembakau pun tak tercium. Anehnya, pita cukai terus mengalir dari pusat.
Maka muncul istilah yang kini viral di lingkaran aktivis dan pengamat industri: ternak pita cukai. Mereka tak sedang produksi, tetapi sedang memerah sistem.
Secara sederhana, pabrik-pabrik ini seperti kandang sapi modern. Tapi bukan sapi yang dipelihara, melainkan kuota cukai. Bukan untuk diolah, tapi untuk dijual kembali dalam bentuk “izin” yang kemudian dipakai untuk membungkus rokok dari pabrik lain yang tak terdaftar.
Model ini sangat menguntungkan karena sistem perizinan pita cukai yang masih longgar ditambah “kompromi manis” dari lembaga pengawas. Bea Cukai? Ah, di warung kopi ada istilah baru: “duduk manis di bawah ketiak pengusaha.”
Kalimat itu terdengar kasar. Tapi begitulah rasa frustrasi masyarakat yang melihat hukum seperti bisa ditekuk. Ketika pabrik zombie bisa mengajukan pita cukai tanpa benar-benar memproduksi, maka jelas ada celah yang dibuka secara sengaja, bukan sekadar karena pengawasan lemah tapi karena “kemauan untuk mengawasi” sudah hilang.
Praktik ini bukan hanya ilegal secara moral, tapi destruktif bagi ekonomi lokal. Tidak ada penyerapan tenaga kerja. Tidak ada distribusi manfaat ke petani tembakau. Tidak ada dampak ekonomi nyata ke desa-desa tempat pabrik berdiri. Mereka hanya jadi penonton pabrik sepi yang kadang bikin macet dan menciptakan harapan palsu.
Coba kita telusuri siapa yang sebenarnya diuntungkan? Bukan buruh, karena mereka tidak dipekerjakan. Bukan petani karena tembakaunya tidak dibeli. Bukan pemerintah daerah karena PAD nihil. Bukan masyarakat sekitar karena yang tersisa hanya gedung bisu tanpa suara ekonomi.
Satu-satunya yang tersenyum adalah mereka yang bisa memainkan angka, mereka yang jago merangkai narasi “peningkatan ekonomi lokal” hanya untuk meloloskan jatah pita cukai. Dan mereka yang tahu pintu mana yang harus diketuk di kantor Bea Cukai dengan meminjam istilah populer “bisik manja.”
Bisik manja para sultan, begitu obrolan warung menyebutnya adalah modus komunikasi informal antara pengusaha dan aparat. Lucu memang, tapi efeknya tragis: hukum tak lagi sakral, pengawasan jadi basa-basi dan sistem negara bisa ditawar.
Di atas kertas, semuanya sah. Tapi di lapangan: nihil. Maka lahirlah ironi di mana negara memberikan izin untuk produksi, tapi yang diproduksi bukan barang, melainkan celah hukum.
Sumenep sedang berada di titik krusial. Jika praktik ini terus dibiarkan, maka ia akan tumbuh menjadi sistem yang permanen, sebuah ekonomi palsu yang tampak hidup tapi sebenarnya menipu. Dan bila Bea Cukai terus diam, maka diam itu bukan lagi pasif, melainkan diduga partisipatif.
Pemerintah pusat boleh saja bicara soal transparansi, transformasi industri dan digitalisasi pengawasan. Namun, semua jargon itu akan jatuh seperti daun tua jika di tingkat daerah pabrik-pabrik kosong tetap mendapat jatah pita cukai.
Di sinilah suara warung kopi punya peran penting. Di saat forum resmi penuh basa-basi dan siaran pers dikemas untuk menyenangkan pejabat, suara warung justru jadi alarm sosial yang paling jujur.
Karena warung memang tidak punya notulensi. Tapi dari sana, suara rakyat kerap lahir tanpa sensor. Dan hari ini, suara itu sedang menggema: “Negara sedang dikalahkan oleh pabrik kosong.”
Dari konklusi kisah dramatis Bollywood tersebut, sosok Anjali memilih diam. Tetap berharap tapi tahu diri: cintanya tak dianggap karena Rahul sudah memilih Tina bukan karena Tina lebih baik, tapi karena Tina tahu caranya bermain sistem. Maka Anjali menjauh bukan karena tak cinta, tapi karena tak diberi ruang.
Hari ini, masyarakat seperti Anjali: tertunduk. Tapi masih sadar bahwa cinta yang tulus tidak cukup jika negara lebih memilih berpaling pada suara yang berbisik.
Jurnalis Serikat News Sumenep, Jawa Timur
Menyukai ini:
Suka Memuat...