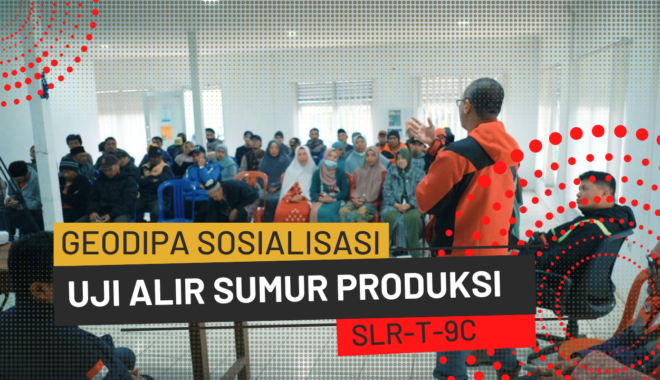Oleh: M. Hanif Dhakiri (Alumni Ponpes al-Muayyad Surakarta; Wakil Ketua Umum DPP PKB)
DI TENGAH riuhnya zaman digital, pesantren kembali disorot. Sayangnya, sering dalam bingkai yang keliru. Dalam tayangan dan percakapan publik belakangan ini, pesantren digambarkan dengan nada merendahkan: sebagai tempat tertutup, kuno, bahkan tidak manusiawi. Narasi semacam itu muncul dari jarak pandang yang tak paham ruhnya. Mereka menilai pesantren dengan kacamata industri hiburan, bukan kebudayaan dan kemanusiaan.
Padahal, sejak berabad-abad lalu, pesantren justru menjadi ruang sunyi tempat ilmu, adab, dan kebijaksanaan bertemu. Ia tumbuh di jantung masyarakat, membentuk manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berjiwa pengabdian. Pesantren lebih tua dari republik, namun paling muda dalam semangatnya: selalu berubah, selalu berbenah, tanpa kehilangan akar.
Sebagaimana ditulis Zamakhsyari Dhofier (2011), pesantren adalah subkultur mandiri, sebuah sistem sosial dan spiritual yang hidup dari keikhlasan, gotong royong, dan ilmu yang dibingkai adab. Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid) (1988) menyebut pesantren sebagai “laboratorium kemanusiaan”: tempat manusia belajar menjadi manusia sebelum menjadi apa pun yang lain. Di ruang ini, ilmu tidak dikejar untuk status, tapi untuk keutuhan diri; guru tidak disembah, tapi dihormati karena keteladanan dan pengorbanannya.
Belajar Menjadi Manusia
Sikap hormat dan kepatuhan dalam pesantren sering disalahartikan sebagai feodalisme. Padahal, ta’dzim kepada kyai bukan bentuk tunduk pada manusia, melainkan latihan spiritual untuk menundukkan ego. Santri kerja bakti (ro’an), menyapu halaman, mencuci piring, membantu dapur, bukan karena diperintah, tetapi karena berkhidmah: melatih diri dalam kesabaran, disiplin, dan kesederhanaan. Nilai-nilai seperti ini jarang ditemukan dalam pendidikan modern yang serba kompetitif. Pesantren menanamkan kesadaran bahwa belajar bukan sekadar menghafal ilmu, tetapi menata diri agar layak menerima ilmu.
Relasi antara kyai dan santri pun bukan relasi kuasa, melainkan relasi moral. Kyai dihormati bukan karena status sosial, tapi karena keteladanan, keilmuan dan kesetiaan pada nilai-nilai luhur. Hubungan itu dilandasi cinta ilmu, bukan rasa takut. Karena itu, tudingan bahwa pesantren menjadi ladang kekayaan bagi kyai jelas menyesatkan.
Sebagian besar pesantren lahir dari tanah wakaf, infak, dan kerja sosial umat. Banyak kyai hidup sederhana: menjadikan rumah pribadinya sebagai asrama, mengajar tanpa gaji, dan mengabdikan hidup untuk mendidik generasi. Jika kini sebagian pesantren tampil modern dengan fasilitas lebih baik, itu bukan tanda kemewahan, tetapi buah kemandirian dan solidaritas sosial. Pesantren membuktikan bahwa ekonomi bisa tumbuh dari keikhlasan, dan modernitas bisa berjalan seiring spiritualitas. Dari keikhlasan lahir kekuatan, dari pengabdian tumbuh kemandirian.
Demokrasi, Kebangsaan, dan Moderasi
Pesantren adalah sekolah demokrasi paling tua di Nusantara. Di dalamnya, anak petani dan pejabat, anak orang kaya dan orang miskin, anak kota dan desa, hidup setara. Semua tunduk pada ilmu dan adab, bukan status sosial. Dari bilik-bilik itu tumbuh egalitarianisme spiritual, yakni keyakinan bahwa kemuliaan diukur bukan dari kekuasaan, tetapi dari pengabdian.
Nilai ini menubuh dalam sejarah kebangsaan. Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari mendirikan Nahdlatul Ulama (NU) dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan semangat kemerdekaan spiritual. KH Wahid Hasyim menjembatani Islam dan kebangsaan dalam perumusan UUD 1945, sekaligus memperbarui pendidikan Islam agar sejalan dengan cita-cita nasional. Sementara Gus Dur memperluas horizon pesantren menjadi kekuatan moral dan sosial yang menegakkan demokrasi, kemanusiaan, dan pluralisme (Wahid, 2006). Mereka menjadikan Islam bukan ideologi eksklusif, melainkan etika publik yang menyatukan.
Kaidah ushul fiqh (prinsip keilmuan Islam) yang berbunyi “al-muhafazhah ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhdu bi al-jadid al-ashlah” (mempertahankan yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik) menjadi napas perubahan yang beradab dan berakar pada tradisi. Karena itu, pesantren tidak menolak modernitas, tetapi menempatkannya di bawah bimbingan moral. Dalam masa ketika agama sering dijadikan alat untuk sensasi atau politik, pesantren justru menampilkan wajah Islam yang teduh, cerdas, dan manusiawi. Ia lembut tapi tegas, terbuka tapi berakar.
Pesantren dan Masa Depan
Pesantren tidak perlu diajari beradaptasi; mereka telah melakukannya selama berabad-abad. Dari surau menjadi universitas, dari langgar menjadi lembaga sosial, dari kitab kuning lahir diskursus ekonomi, lingkungan, dan teknologi. Adaptasi itu bukan bentuk kehilangan jati diri, melainkan manifestasi dari prinsip ijtihad, memperbarui bentuk tanpa meninggalkan ruh.
Kini banyak pesantren menjadi pusat kewirausahaan sosial, pendidikan vokasi, hingga gerakan ekologi berbasis iman. Semua dilakukan dengan satu tujuan: membumikan ilmu, memanusiakan manusia. Pesantren menolak dikotomi antara dunia dan akhirat, antara sains dan agama. Ia menegaskan kembali bahwa kemajuan sejati bukan diukur oleh kecepatan teknologi, tetapi oleh kedalaman moral dan ketulusan budi.
Serangan dan stereotip terhadap pesantren belakangan ini justru memperlihatkan satu hal: bahwa pesantren masih relevan, karena ia tetap menjadi cermin nurani bangsa. Dan selama pesantren berdiri, selama para kyai menyalakan pelita ilmu dengan keikhlasan, Indonesia tidak akan kehilangan arah. Sebab di setiap denyut pesantren, selalu ada doa yang menegakkan langit dan kemanusiaan.
SerikatNews.com adalah media kritis anak bangsa. Menyajikan informasi secara akurat. Serta setia menjadi platform ruang bertukar gagasan faktual.
Menyukai ini:
Suka Memuat...